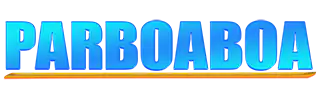PARBOABOA, Jakarta - Teater Utan Kayu pada Sabtu (26/04/2025) sore tampak berbeda. Puluhan orang dari berbagai profesi dan latar belakang berdesakan di sepanjang koridor hingga di dalam ruangan teater.
Dengan langkah tertatih, Goenawan Mohamad masuk dan mengambil posisi duduk di depan. Ia mengenakan topi pet andalan dan baju kemeja ala kadarnya. Tangan kanannya menggenggam sebuah tongkat.
GM, demikian ia disapa, tampaknya tak benar-benar uzur. Ia masih seperti pemikir muda belia yang gemar menghabiskan waktu dengan membaca dan menulis. Karya-karyanya hidup di hati pembaca.
Setelah debutnya sebagai novelis dengan "Surti + Tiga Sawunggaling" pada 2018 lalu, kini, di usia 84 tahun, ia kembali mempersembahkan novel keduanya berjudul "Manurung: Sebuah Montase".
Seorang pengujung, entah siapa, berbicara di sela-sela diskusi bahwa momentum peluncuran tersebut menjadi pertanda bahwa kreativitas tidak pernah mengenal batas waktu.
"Di luar dunia sastra, GM ini aktif dalam seni rupa, melukis, membuat karya grafis, dan instalasi," ucap orang itu seperti memberi penjelasan kepada seorang kawan.
Penjelasan itu beralasan. GM, di usia yang tak lagi mudah masih sering berkarya. Ia membuat apa saja yang menurut isi kepalanya berguna untuk diri sendiri dan orang di sekitar.
"Makanya dia kelihatan segar. Bahasa Inggrisnya juga fasih. Padahal, usianya itu sudah sangat tua loh. Coba bayangkan saja," ungkap orang itu lagi.
Ditemani Ayu Utami sebagai pembicara, keseluruhan diskusi berlangsung hangat. Berbagai pertanyaan dilontarkan pengunjung untuk menggali latar belakang dan tujuan cerita.
Para pengunjung lain memilih diam sambil menimang-nimang pembicaraan Ayu. Di tangan mereka, "Manurung: Sebuah Montase", dibiarkan terbuka untuk lembar-lembar sekian.
Manurung: Sebuah Montase
Dalam paparannya, Ayu menjelaskan bahwa karya GM ini berisi perjalanan dua saudara eksil Indonesia, Karel dan Yosef, yang terpisah akibat peristiwa 1965 sehingga mengubah nasib keluarga mereka.
Ayah mereka dibunuh dalam penumpasan PKI, dan kedua saudara ini terdampar di Eropa Timur. Karel terlempar ke Jerman Timur, sedangkan Yosef ke Cekoslowakia.

Karel yang direkrut oleh Stasi (badan intelijen Jerman Timur) kemudian terlibat dalam dunia spionase, sementara Yosef adiknya, terjebak dalam peristiwa "Musim Semi Praha" pada 1968.
Peristiwa ini, meminjam ungkapan GM dalam karyanya, adalah sebuah pemberontakan singkat yang menentang dominasi Uni Soviet.
Karel yang dihantui rasa rindu dan kecemasan harus menghadapi tugas dari badan intelijen untuk "menghidupkan kembali komunisme" di Indonesia.
Namun, pencarian Karel terhadap Yosef bukan hanya soal menyatukan kembali keluarga, tetapi juga mengungkap ketegangan antara harapan, kebingungan, dan bahaya yang mengancamnya.
Seperti tulisan GM lainnya, Manurung tidak hanya berfokus pada plot, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan tema-tema besar seperti ideologi, kemanusiaan, dan sistem sosial-politik.
Dialog dan surat-menyurat antar para tokoh menjadi wahana bagi GM untuk menggugah perenungan filosofi yang mendalam, yang juga kerap ia hadirkan dalam Catatan Pinggir-nya.
Lebih lanjut, Ayu bilang bahwa "Manurung" merupakan karya penting yang membawa pembaca untuk tidak melupakan sejarah Perang Dingin, meskipun banyak yang menganggapnya telah berlalu.
“Perang Dingin, meskipun sudah dianggap usai, sesungguhnya masih membentuk dunia kita hari ini,” ujar Ayu.
Runtuhnya Uni Soviet dan blok Timur pada akhir 1980-an memang disambut dengan harapan akan kemenangan demokrasi, namun menandai munculnya perang dan kekerasan baru yang diselimuti nama agama, etnisitas, dan kapitalisme yang tak terkendali.
Perdebatan tersebut, meski tidak langsung menyentuh pasca-Perang Dingin, tetap relevan dalam percakapan-percakapan para tokohnya yang mengkritik sistem kapitalisme maupun sosialisme.
Salah satu aspek menarik dalam novel ini, pungkas Ayu, adalah bagaimana GM menghadirkan percakapan tentang kapitalisme dan komunisme.
Kritik terhadap kapitalisme mengalir melalui tokoh Karel dan atasannya, Farhad Hamedani, seorang pelarian dari Iran, yang mendiskusikan arsitektur sebagai ruang menciptakan kepercayaan dan solidaritas antar manusia.
Hal ini disebut Farhad berbeda dengan pandangan kaum borjuis yang melihat arsitektur sebagai hasil desain semata.
“Di sini arsitektur perjuangan menciptakan ruang agar manusia saling percaya, saling ketemu, saling membantu,” kata Farhad kepada Karel.
Sementara itu, dalam perbincangan tokoh-tokoh lainnya, seperti Yosef dan Renatka, kritik terhadap komunisme juga disuarakan.
Renatka yang berjuang melawan kekejaman Partai Komunis Cekoslovakia, memberikan pandangan bahwa yang dibutuhkan bukanlah “pendekar perang,” melainkan “kemauan politik” yang terkadang ada, terkadang tidak.
Percakapan filosofis yang terjalin lembut namun penuh makna ini tidak hanya memperkaya alur cerita, tetapi juga mengajak pembaca merenung lebih jauh tentang maksud di balik kebijakan politik yang mempengaruhi kehidupan banyak orang.
Gaya Penulisan
Selain berbicara tentang penokohan, Ayu juga memberikan apresiasi tinggi terhadap gaya penulisan GM yang puitis dan fragmentaris.
Dalam Manurung, GM mengadopsi struktur montase, yakni sebuah bentuk yang terdiri dari potongan-potongan cerita yang berhubungan tidak secara linier, tetapi lebih asosiatif.
Hal ini menciptakan sebuah suasana melankolis yang menyeluruh, sesuai dengan judul dan nama tokoh, Manurung, yang mencerminkan renungan yang murung.
Menurut Ayu, GM memanfaatkan bentuk montase ini untuk menggambarkan kesadaran akan "kemustahilan bahasa." Bahwa bahasa, sebagai alat berpikir, tidak cukup memadai untuk mengungkapkan seluruh kedalaman pemikiran dan perasaan.
Dalam karyanya, GM mempertanyakan dan mengkritik keterbatasan bahasa, sembari tetap mempertahankan rasionalitas.
"Ini membedakan karyanya dari novel-novel yang terjebak dalam depresi mental tanpa pencarian filosofis yang mendalam," tandas Ayu.
Perjalanan Intelektual GM
Goenawan Mohamad lahir di Batang pada 29 Juli 1941. Ia adalah seorang pejuang pemikiran yang telah melintasi banyak medan, dari dunia jurnalistik hingga sastra dan seni rupa.
Sebagai pendiri majalah Tempo, Goenawan tidak hanya dikenal karena kontribusinya dalam dunia jurnalistik, tetapi juga komitmennya dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berdemokrasi.
Di sepanjang perjalanan hidupnya, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketika majalah Tempo dibredel pada 1994 oleh pemerintah Orde Baru (Orba).
Namun, Goenawan tetap teguh pada prinsip-prinsipnya, dan kontribusinya terhadap sastra serta pemikiran kritis di Indonesia mendapat pengakuan internasional.
Sebagai seorang penulis, Ayu menyebut bahwa Goenawan telah menciptakan standar baru dalam sastra Indonesia, di mana ia berhasil menggabungkan bahasa yang puitis dengan pemikiran yang mendalam.
Karya-karyanya terus menginspirasi banyak orang. "Dengan Manurung: Sebuah Montase", Goenawan kembali menunjukkan bahwa kreativitas tidak mengenal batas usia.
Novel ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi sebuah undangan untuk merenung tentang dunia yang terus berubah.